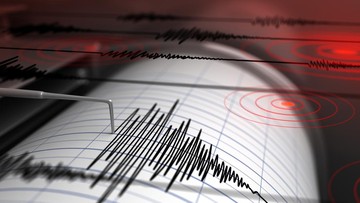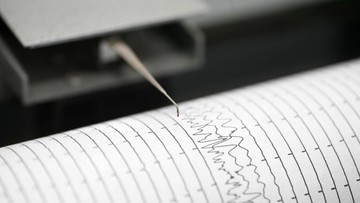LEMBAGA pemantau media sosial Drone Emprit mengungkapkan terjadi perdebatan yang terfragmentasi terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pilkada lewat DPRD.
Berdasarkan pemantauan Drone Emprit pada periode 5 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, ide pengembalian pilkada tidak langsung itu memicu 10.257 percakapan dengan lebih dari 9,19 juta interaksi lintas platform. “Angkanya besar, emosinya kuat, tetapi arahnya terfragmentasi,” kata pendiri media kernel Drone Emprit, Ismail Fahmi, pada Rabu, 7 Januari 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Penelusuran Drone Emprit menunjukkan platform X menjadi pusat resistensi paling keras terhadap wacana pilkada lewat DPRD. Dari lebih kurang 7.096 mentions, sekitar 70,3 persen bernada negatif, dengan kata kunci seperti “dirampas”, “Orde Baru”, dan “kembali ke MPR”. Namun, resistensi ini didorong terutama oleh aktivis, akademisi, dan akun publik kritis.
Masalahnya, kata Ismail, bukan pada kekuatan argumen, tetapi pada cakupan sosialnya. Media sosial X menurut dia adalah ruang opini elite-digital. “Ia nyaring, cepat viral, tetapi tidak selalu merepresentasikan mayoritas pemilih secara sosiologis,” ujar Ismail. Dalam kalkulasi politik, ini membuat penolakan terlihat kuat secara moral, tetapi belum tentu menentukan secara elektoral.
Sementara itu, Facebook dan Instagram menunjukkan penolakan yang tidak solid dan lebih ambigu. Sentimen negatif terhadap wacana pilkada tidak langsung di Instagram mencapai 49,7 persen, sedangkan di Facebook mendekati 50 persen. Tetapi, sentimen positif tetap signifikan di kisaran 30 persen.
Menurut Ismail, ini menunjukkan bahwa publik tidak sepakat tentang apa yang salah dan apa solusinya. Di kedua platform itu, Ismail berujar, banyak yang mengeluh pilkada langsung mahal, melelahkan, dan penuh konflik, namun pada saat bersamaan mereka ragu menyerahkan pilihan kepada DPRD. “Kebimbangan ini adalah wilayah abu-abu, dan wilayah abu-abu adalah ladang manuver politik,” kata dia.
Di lain sisi, pemantauan terhadap platform YouTube menunjukkan sentimen positif sebesar 51 persen dan negatif 29,5 persen. TikTok mencatat 41,6 persen sentimen positif dengan interaksi tertinggi, yakni 5,59 juta. Ismail mengatakan data ini penting karena kedua platform tersebut menjangkau audiens luas di luar komunitas aktivis.
Di YouTube dan TikTok, wacana pilkada oleh DPRD tidak selalu dibaca sebagai pengkhianatan demokrasi, melainkan sebagai opsi kebijakan yang sah untuk diperdebatkan. “Ketika suatu gagasan sudah masuk fase “boleh diperdebatkan”, secara politik ia sudah melewati pintu pertama penerimaan publik,” tutur Ismail.
Sementara itu, di media online arus utama, sentimen mengenai pilkada oleh DPRD justru mayoritas positif, yakni sebesar 52,6 persen. Sedangkan sentimen negatif tercatat 30,8 persen. Dari 1.629 artikel, narasi efisiensi anggaran, konstitusionalitas, dan stabilitas politik mendominasi.
“Sering kali kita mengira kegaduhan di media sosial berarti kemenangan opini publik. Data menunjukkan sebaliknya,” kata Ismail. Ia mengingatkan bahwa kegaduhan tanpa konsensus justru membuka ruang keputusan elite. Ismail menilai media sosial memang berisik, tetapi belum menjadi satu suara yang memaksa perubahan arah kebijakan.
Menurut Ismail, apabila pendukung pilkada langsung tidak mampu mengubah kegelisahan digital menjadi konsensus sosial yang luas, maka peluang pilkada oleh DPRD justru semakin besar. “Dan dalam politik, yang paling berbahaya bukan penolakan keras, melainkan penolakan yang tercerai-berai,” kata Ismail.